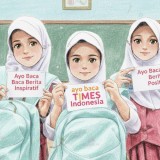TIMES SITUBONDO, SITUBONDO – Usulan pemberangkatan jamaah haji Indonesia melalui jalur laut kembali menjadi sorotan publik. Menteri Agama membuka peluang dibukanya transportasi laut sebagai opsi tambahan selain jalur udara yang selama ini digunakan.
Ide ini mengundang rasa ingin tahu sekaligus perdebatan. Ada yang menyambutnya sebagai solusi untuk efisiensi biaya dan peningkatan kuota, tetapi tak sedikit pula yang mempertanyakan kelayakannya secara teknis, logistik, hingga urgensinya dalam konteks pelayanan jamaah haji hari ini.
Gagasan ini tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pelayaran haji Indonesia di masa lalu. Sebelum 1970-an, jutaan jamaah menempuh perjalanan laut selama puluhan hari menggunakan kapal seperti Gunung Jati atau Belle Abeto menuju Jeddah. Perjalanan tersebut sarat makna, tapi juga penuh tantangan.
Kini, di era transportasi udara yang mampu membawa jamaah hanya dalam 9–10 jam, munculnya wacana haji laut memunculkan pertanyaan penting: apakah ini benar-benar solusi yang rasional, atau hanya romantisme masa lalu yang dipaksakan ke masa kini?
Antara Efisiensi dan Realitas
Salah satu alasan pemerintah mempertimbangkan jalur laut adalah potensi efisiensi biaya. Namun, narasi efisiensi ini patut ditinjau ulang secara objektif.
Perjalanan laut memerlukan waktu sekitar dua minggu satu arah, artinya logistik seperti makanan, air bersih, listrik, dan layanan medis harus disediakan dalam durasi yang jauh lebih lama. Ini belum termasuk kebutuhan kru kapal, bahan bakar, serta potensi keterlambatan akibat cuaca buruk.
Lembaga seperti BPKH maupun BP Haji justru mengingatkan bahwa jalur laut bisa berbiaya lebih tinggi dibanding udara, jika semua komponen dihitung secara menyeluruh.
Selain itu, mayoritas jamaah haji Indonesia kini berusia lanjut. Data resmi menunjukkan lebih dari 60 persen jamaah adalah kelompok usia 60 tahun ke atas. Menempatkan mereka dalam perjalanan panjang di laut dengan kemungkinan keterbatasan layanan medis akan menjadi tantangan besar.
Gagasan bahwa perjalanan laut dapat menggantikan jalur udara dalam skala massal perlu ditinjau secara hati-hati, karena bisa berimplikasi langsung pada keselamatan dan kenyamanan jamaah.
Kesiapan Armada dan Infrastruktur
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan teknis. Hingga kini, Indonesia belum memiliki kapal penumpang berskala besar yang didesain untuk mengangkut ribuan jamaah dengan fasilitas lengkap dan standar internasional.
Operator pelayaran swasta yang menyatakan minat masih mengandalkan opsi menyewa kapal asing, yang justru membuka risiko biaya tambahan, regulasi lintas negara, dan pengawasan yang rumit.
Demikian pula pelabuhan-pelabuhan di Indonesia belum disiapkan sebagai terminal embarkasi haji laut. Proses imigrasi, karantina, hingga pengawasan kesehatan di pelabuhan masih belum terintegrasi secara optimal.
Bahkan menurut pernyataan dari Kementerian Perhubungan, rencana ini membutuhkan kajian mendalam lintas sektor dan waktu yang tidak singkat. Artinya, dalam kondisi saat ini, usulan ini masih lebih banyak menghadapi hambatan dibanding peluang.
Ada pula narasi bahwa jalur laut dapat membuka peluang penambahan kuota haji dari Arab Saudi. Memang benar, Saudi berencana meningkatkan total jamaah menjadi 5 juta orang pada 2030. Namun, kuota haji nasional tetap ditentukan oleh banyak faktor diplomasi, kapasitas pelayanan, serta rekam jejak negara pengirim.
Moda transportasi bukan faktor utama penentu kuota. Karenanya, berharap pada penambahan kuota melalui jalur laut terlalu dini jika tidak didukung pendekatan diplomatik yang kuat.
Opsi Terbatas, Bukan Kebijakan Massal
Meski demikian, jalur laut tetap bisa dijajaki dalam skala terbatas sebagai opsi tematik. Misalnya, paket “napak tilas haji” bagi kalangan muda dan sehat yang ingin merasakan pengalaman spiritual lebih panjang.
Skema ini dapat dijalankan secara pilot project, dengan pengawasan ketat dan keterlibatan swasta yang benar-benar siap. Dengan pendekatan ini, kita tidak memaksakan jalur laut sebagai kebijakan massal, tetapi menjadikannya pelengkap, bukan pengganti.
Yang tidak boleh dilupakan adalah pengawasan terhadap pelaksanaannya. Jangan sampai jalur laut dimonopoli oleh satu operator atau dijalankan tanpa transparansi. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap moda yang digunakan dalam pelayanan ibadah haji tunduk pada prinsip keadilan, keterjangkauan, dan keselamatan jamaah.
Sementara itu, jalur udara yang selama ini digunakan tetap perlu dibenahi. Pemerintah semestinya fokus mempercepat reformasi pelayanan udara, dari pemangkasan masa tinggal jamaah, perbaikan sistem katering dan akomodasi, hingga transparansi biaya. Pembenahan yang menyentuh langsung kebutuhan mayoritas jamaah lebih mendesak ketimbang membuka jalur baru yang belum siap.
Usulan haji jalur laut bukan sesuatu yang keliru, tetapi tidak otomatis menjadi solusi. Gagasan sebesar ini harus ditopang oleh kesiapan infrastruktur, kelayakan finansial, serta keberanian mengevaluasi secara objektif. Jika tidak, alih-alih menjadi terobosan, ia justru bisa menjadi sumber masalah baru.
Selama belum ada kepastian biaya, kesiapan kapal, dan desain pelayanan yang memadai, wacana ini belum cukup kuat untuk dijadikan kebijakan nasional.
Untuk saat ini, lebih bijak jika haji jalur laut tetap ditempatkan sebagai ide terbuka yang terus dikaji, bukan sebagai solusi instan atas kompleksitas penyelenggaraan haji. Tanpa kesiapan menyeluruh, ide ini masih lebih dekat sebagai ilusi daripada solusi.
***
*) Oleh : Nur Kamilia, Dosen Hukum STAI Nurul Huda Situbondo.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |