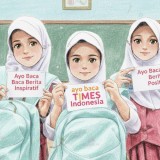TIMES SITUBONDO, SITUBONDO – Di banyak kota besar Indonesia, pemandangan orang berkerumun dengan spanduk, toa, dan orasi bukanlah hal baru. Dari isu undang-undang kontroversial, kenaikan harga, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan, jalanan kerap menjadi ruang ekspresi publik. Demo telah menjelma sebagai bahasa politik yang paling mudah dikenali.
Namun, pertanyaan menarik muncul: bagaimana demo dipersepsikan publik luas yang tidak hadir di lapangan? Jawabannya ada pada media.
Di era ketika televisi, portal berita, dan media sosial menjadi penyalur utama informasi, wajah sebuah demo kerap lebih ditentukan oleh bingkai kamera dan pilihan redaksi daripada oleh orator di depan pagar gedung DPR.
Fenomena ini mengundang refleksi: apakah media membantu publik memahami substansi protes, atau justru menjadikan demo sekadar tontonan rutin, sensasional, bahkan melelahkan?
Demo di Mata Media Arus Utama
Liputan demo di media arus utama biasanya mengulang pola yang sama: fokus pada jumlah massa, kemacetan, dan yang paling sering kericuhan. Kamera televisi lebih senang menyorot adegan bakar ban, bentrokan dengan aparat, atau wajah-wajah emosional yang sedang berteriak. Tuntutan substantif, data yang mendasari protes, dan konteks sosial seringkali tenggelam di balik visual dramatis.
Pola ini bukan semata pilihan estetika. Secara struktural, media kita tumbuh dengan logika industri: berita yang dramatis akan menarik lebih banyak penonton. Maka, “massa ricuh” lebih mudah dijual daripada “massa menuntut revisi pasal sekian”.
Dampaknya, publik yang menyaksikan dari rumah atau membaca portal berita bisa membentuk persepsi keliru. Demo dipandang identik dengan chaos, kerumunan tanpa arah, atau bahkan kegiatan sia-sia yang hanya menambah macet kota. Padahal, bagi para peserta demo, itu adalah ekspresi politik yang sah, bahkan vital bagi demokrasi.
Media Sosial Arena Penuh Tantangan
Kemunculan media sosial memberikan ruang berbeda. Peserta demo kini bisa menyiarkan langsung jalannya aksi, membagikan poster digital, hingga mengunggah narasi personal tentang mengapa mereka turun ke jalan. Bagi banyak orang, ini menjadi koreksi atas framing media arus utama yang kerap menyepelekan isi tuntutan.
Namun, media sosial bukan tanpa masalah. Di balik narasi alternatif, ada juga risiko disinformasi, provokasi, hingga polarisasi opini. Kadang, video potongan singkat lebih viral daripada penjelasan panjang yang detail. Hasilnya, demo bisa tereduksi lagi menjadi bahan perdebatan panas tanpa substansi.
Hal ini membuat publik dihadapkan pada paradoks: di satu sisi, media sosial memperkaya perspektif; di sisi lain, ia juga bisa memperkeruh, membuat protes lebih tampak sebagai ajang perang opini ketimbang ruang dialog.
Framing dan Dampaknya terhadap Demokrasi
Mengapa framing media penting? Karena cara media menyajikan demo akan mempengaruhi bagaimana publik memahami hubungan antara negara dan warganya.
Bila demo selalu digambarkan negatif, stigma “aksi jalanan” akan semakin kuat: seolah-olah protes adalah pengganggu ketertiban, bukan bagian dari demokrasi.
Sebaliknya, bila media berani mengangkat substansi tuntutan, memperlihatkan wajah manusiawi demonstran, dan memberi ruang pada konteks, publik akan lebih mudah melihat demo sebagai bagian sah dari partisipasi politik.
Sayangnya, kecenderungan media arus utama masih berkutat pada logika klik dan rating. Suara rakyat jarang hadir dalam bentuk mendalam, sementara visual kericuhan selalu mendapat tempat. Akibatnya, demokrasi berisiko terjebak pada permukaan: bising di layar, tapi hening dalam pemahaman.
Dari Spektakel ke Substansi
Media punya tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Liputan demo seharusnya tidak berhenti pada visual dramatis atau kutipan sekilas. Ada kebutuhan untuk menghadirkan konteks: mengapa orang turun ke jalan, apa yang dipersoalkan, bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Bukan berarti kericuhan harus diabaikan. Namun, menampilkan kericuhan tanpa menyinggung akar masalah sama saja menjadikan demo sekadar tontonan. Demokrasi akhirnya hanya dipersepsi sebagai adu teriak, bukan perdebatan ide.
Selain itu, media perlu memperhatikan representasi. Selama ini, wajah demonstran yang sering muncul adalah mahasiswa laki-laki berteriak. Padahal, ada perempuan, buruh, petani, bahkan pelajar yang ikut serta.
Membuka ruang bagi keragaman wajah demonstran akan membuat publik lebih melihat demo sebagai ekspresi masyarakat luas, bukan sekadar kelompok tertentu.
Tidak adil bila beban sepenuhnya dipikul media. Publik juga punya tanggung jawab kritis. Alih-alih hanya mengeluh tentang macet akibat demo, masyarakat bisa mencoba memahami substansi tuntutan. Membaca lebih jauh, mencari sumber informasi alternatif, atau bahkan berdialog dengan peserta aksi adalah bagian dari literasi politik.
Demo di Indonesia, seperti di banyak negara lain, tidak akan hilang. Ia adalah denyut nadi demokrasi sekaligus pengingat bagi penguasa bahwa rakyat masih punya suara. Namun, cara kita melihat demo kini sangat bergantung pada media.
Bila media terus-menerus menyorot sisi sensasional, publik akan semakin jauh dari substansi. Tapi bila media berani mengambil peran sebagai penerjemah aspirasi, bukan sekadar penyaji drama, demokrasi kita bisa lebih sehat.
Di tengah kebisingan layar dan jalanan, tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan suara rakyat tidak berhenti menjadi gema kosong. Pada akhirnya, demokrasi bukan soal seberapa keras teriakan terdengar, melainkan seberapa dalam maknanya dipahami. (*)
***
*) Oleh : Nur Kamilia, Dosen Hukum STAI Nurul Huda Situbondo.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |