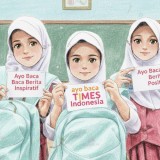TIMES SITUBONDO, SITUBONDO – Pada awal September 2025, publik ekonomi Indonesia kembali diguncang oleh pengumuman mengejutkan: Bank Indonesia (BI) sepakat menjalankan skema burden-sharing dengan pemerintah.
Kesepakatan ini mencakup kenaikan bunga simpanan pemerintah di bank sentral serta komitmen dukungan pembiayaan untuk program perumahan rakyat dan koperasi desa.
Bagi sebagian orang, langkah ini dianggap strategis bukti sinergi fiskal dan moneter demi kepentingan rakyat. Namun bagi kalangan lain, terutama ekonom dan pelaku pasar, ini adalah sinyal bahaya.
Mengapa? Karena independensi bank sentral, fondasi utama kepercayaan pasar, kini seakan berada di persimpangan jalan: antara menjaga stabilitas moneter atau menjadi perpanjangan tangan kebijakan fiskal.
Independensi Bank Sentral
Sejak reformasi 1999, Bank Indonesia dirancang sebagai lembaga independen. Mandat utamanya jelas: menjaga stabilitas rupiah, baik nilai tukar maupun inflasi.
Independensi ini bukan sekadar formalitas hukum, tetapi pelajaran mahal dari krisis 1997–1998, ketika BI dipaksa membiayai defisit fiskal dan akhirnya memicu kejatuhan rupiah.
Dengan independensi, BI diharapkan bebas dari intervensi politik jangka pendek. Investor percaya bahwa kebijakan moneter Indonesia akan konsisten dan kredibel. Begitu kredibilitas ini runtuh, pasar finansial bisa bereaksi cepat dan brutal.
Apa Itu Burden-Sharing?
Burden-sharing secara sederhana adalah pembagian beban pembiayaan antara pemerintah dan bank sentral. Dalam praktiknya, hal ini bisa berupa pembelian obligasi pemerintah oleh BI, penyesuaian bunga simpanan pemerintah, atau dukungan langsung pada program-program tertentu.
Pada masa pandemi 2020, skema ini dilakukan dengan dalih keadaan darurat. Kala itu, BI menanggung sebagian beban bunga surat utang pemerintah untuk menutup defisit akibat belanja kesehatan. Alasan tersebut dipandang masuk akal: kesehatan publik memang prioritas.
Namun, pada 4 September 2025, BI kembali mengumumkan langkah serupa. Kali ini alasannya bukan darurat global, melainkan untuk mendukung program perumahan rakyat dan koperasi (Reuters, 4 September 2025).
Pertanyaannya, apakah justifikasi kali ini cukup kuat untuk melibatkan kembali BI dalam ranah fiskal?
Risiko yang Mengintai
Ada setidaknya tiga risiko besar jika independensi BI tergerus oleh praktik burden-sharing.
Kedua, Ancaman Inflasi. Jika bank sentral terlalu banyak menanggung beban fiskal, kapasitasnya menjaga stabilitas harga akan melemah. Pengalaman negara lain menunjukkan hal ini.
Turki, misalnya, mengalami inflasi lebih dari 50% ketika bank sentralnya ditekan pemerintah untuk menurunkan suku bunga demi kepentingan politik.
Kedua, Krisis Kepercayaan Investor. Pasar global menilai tinggi independensi bank sentral. Begitu kredibilitas dipertanyakan, investor bisa menarik dana, memicu capital outflow, dan melemahkan rupiah. Hal ini akan meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan.
Ketiga, Politik Jangka Pendek Mengorbankan Stabilitas Jangka Panjang. Pemerintah selalu punya insentif untuk menggunakan moneter demi kepentingan populis misalnya, menjaga kredit murah menjelang pemilu. Namun kebijakan populis jangka pendek seringkali bertentangan dengan kebutuhan stabilitas jangka panjang.
Pada 8 September 2025, Reuters melaporkan bahwa pemerintah dan BI berusaha meredakan kekhawatiran publik dengan menyatakan independensi tidak akan berkurang (Reuters, 8 September 2025). Namun, publik dan investor tentu menilai bukan dari janji, melainkan dari konsistensi tindakan.
Mengapa Pemerintah Tetap Mendorongnya?
Alasan utama pemerintah adalah kebutuhan fiskal yang mendesak. Backlog perumahan di Indonesia masih sangat besar, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, koperasi desa sering kesulitan mendapatkan akses modal murah.
Dengan melibatkan BI, pemerintah berharap pembiayaan program bisa lebih murah dan cepat. Namun, apakah ini solusi jangka panjang? Bukankah ada alternatif lain, seperti optimalisasi pajak progresif, efisiensi belanja, atau digitalisasi penerimaan negara?
Turki bukan satu-satunya contoh. Argentina juga berkali-kali mengalami krisis mata uang karena bank sentralnya kehilangan independensi, dipaksa mencetak uang demi membiayai defisit fiskal. Hasilnya: hiperinflasi, anjloknya kepercayaan investor, dan rakyat yang menanggung beban.
Sebaliknya, Malaysia dan Thailand berhasil menjaga keseimbangan: memperkuat fiskal melalui pajak baru tanpa mengorbankan independensi moneter. Indonesia semestinya belajar dari kedua tetangga dekatnya ini.
Konteks sosial politik tak bisa diabaikan. Skema ini diumumkan hanya beberapa hari sebelum gelombang protes nasional terkait gaya hidup mewah pejabat DPR.
Publik yang sudah skeptis tentu mudah menghubungkan: di satu sisi pejabat bermewah-mewahan, di sisi lain bank sentral harus “ikut menalangi” program pemerintah.
Jika kepercayaan publik terhadap BI runtuh, dampaknya bisa lebih parah daripada indikator ekonomi apa pun. Karena ekonomi, pada akhirnya, adalah soal psikologi kepercayaan.
Jalan Tengah yang Bisa Dilakukan
Pertama, Transparans Detail Skema. Publik berhak tahu seberapa besar beban yang ditanggung BI, bagaimana mekanisme pengembalian, dan sampai kapan kesepakatan berlaku.
Kedua, Batasan yang Tegas. Kesepakatan ini harus bersifat sementara, dengan garis batas yang jelas. Jangan sampai menjadi kebiasaan permanen setiap kali APBN tertekan.
Ketiga, Keterlibatan Akademisi dan Parlemen. DPR, akademisi, dan masyarakat sipil harus aktif mengawasi. Diskusi publik yang sehat bisa menjadi benteng terakhir independensi BI.
Keempat, Alternatif Pembiayaan. Daripada bergantung pada BI, pemerintah sebaiknya memperluas basis pajak progresif, digitalisasi penerimaan, dan memangkas belanja tidak produktif.
Bank Indonesia kini berada di persimpangan: tetap menjaga independensi sebagai pilar stabilitas jangka panjang, atau mengorbankannya demi memenuhi kebutuhan fiskal jangka pendek.
Sejarah menunjukkan, ketika independensi bank sentral terkikis, yang paling menderita adalah rakyat. Inflasi melonjak, rupiah melemah, dan biaya hidup naik. Karena itu, kita harus jujur bertanya: apakah burden-sharing benar-benar solusi, atau justru jalan pintas yang berisiko?
Keputusan hari ini akan menentukan wajah ekonomi Indonesia di masa depan. Dan masa depan itu tidak bisa dibangun dengan menukar kredibilitas demi kepentingan sesaat.
***
*) Oleh : Nur Kamilia, Dosen Hukum STAI Nurul Huda Situbondo.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |